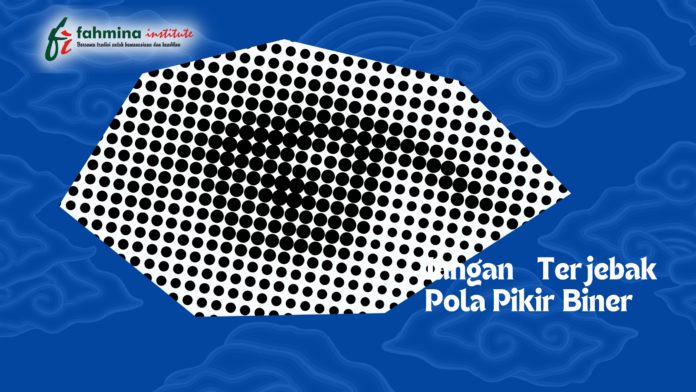Oleh: Faisal Rifki
Pagi Idul Fitri kemarin ada ucapan dari Tacik pemilik toko yang cukup meninju pelipis kiri saya, “Ada apa, tong? Mau ngasih ketupat?” ucapan itu terlontar tak selang lama ia menghambur dari dalam ketika saya mengetuk gerbang tokonya. Namun, mimiknya lekas berubah terkejut ketika saya menanyakan kertas minyak atau kertas wajik untuk tanda berkabung kerabat saya yang wafat tak lama setelah waktu salat Id selesai. Ucapan Taci tersebut membuat saya teringat kembali masa kecil yang saat itu antusias menyambut hari perayaan Imlek, selain kiriman dodol keranjang dari mereka, namun juga tradisi lehongan berupa angpao.
Betapa mereka tak pernah abstain berbagi kebahagiaan tiap hari perayaan etnis mereka. Alasan kenapa merasa pelipis saya berasa tertonjok karena tak pernah saya tahu dari etnis maupun kepercayaan di lingkungan saya mengirimi makanan khas hari perayaan, membagi kebahagiaan. Saya sendiri telat mengetahui kebanyakan kepercayaan apa yang mereka pegang. Aku jadi teringat ucapan Eka Kurniawan, “Indonesia hanya dibagi dua: Jawa dan luar Jawa.” Tak jauh beda akhirnya dengan “Muslim dan non-Muslim”.
Sebenarnya sudah dari orok indikasi untuk memahami tentang agama lain tersedia di sekitar kepala saya. Namun, sudah mafhum masyarakat Indonesia itu gampang mengikat hal-hal menjadi tabu. Bias dari kecenderungan itu menghambat wawasan yang harusnya bisa didapatkan. Masuk jenjang sekolah pun tak kalah bedaya. Sangat minim penjelasan tentang ragam agama maupun kepercayaan. Setidaknya di Indonesia sebagai negara yang majemuk, dan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Negara yang juga berlabel pluralisme dan memegang teguh asas demokrasi. Makan dari itu yang selalu disoroti adalah ukuran mayoritas tadi, padahal menurut Dr. Karlina Supelli, sisi lain dari demokrasi adalah mendengar suara minoritas, dan itu yang terpenting menurut beliau. Suara dari sudut memang terdengar senyap.
Perbedaan sama halnya dengan persamaan. Kita tak bisa menolak apalagi menghilangkan adanya yang biner itu. Entah sudah berapa banyak bibir yang mengucap betapa mengerikannya terjebak pada pikiran biner: salah-benar, baik-buruk, hitam-putih dan tetek bengek lainnya. Padahal yang terpenting itu adalah bagaimana kita bersikap. Pikiran biner itu bisa mengarahkan orang pada pemikiran fundamentalis sampai akhirnya mengakibatkan aksi anarkisme/ekstrimis berlandaskan agama. Teks dibalas teks, menurut Rusdi Mathari, tafsir dibalas tafsir, lanjutnya.
Fanatisme bisa mempersempit cara bersikap kita terkait perbedaan. Bukankah yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi sesuatu. Masyarakat Indonesia sendiri punya selera humor yang tinggi. Tidak mudah terprovokasi. Kasus-kasus yang terjadi terkait gerakan dan aksi teror radikalisme agama justru timbul dari luar Indonesia sendiri. Dibawa oleh orang-orang yang terjebak pemahaman agama yang keliru—untuk menghindari penggunaan kata salah. Sesudah masuk itu mereka kesulitan untuk keluar. Jaringan itu memang pada umumnya terstruktur. Gus Dur sendiri pernah terjerat kontroversi terkait ucapannya bahwa, salam tidak harus menggunakan assalamualaikum. Tapi ucapan itu dipelintir oleh seorang wartawan dengan merubah kata “harus” menjadi “perlu”. Akhirnya, begitu pentingnya memahami bahasa. Apalagi kata bisa memiliki makna yang berbeda, memiliki rumahnya masing-masing di tiap kepala manusia.
Sempat beredar isu kristenisasi bergaya Islam yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks Syria/Suriah (KOS). Karena ibadah mereka dinilai menyerupai ritual ibadah agama Islam. KOS menjalani ibadah shalat, puasa, haji, bahkan dari umat perempuannya sendiri diwajibkan untuk memakai hijab. Sebenarnya, situasinya jadi runyam karena kekurangtahuan kita terkait isu yang dibicarakan. Kita hanya ikut-ikutan kekeliruan yang beredar. Padahal KOS sendiri ada dari abad ke-5, satu abad sebelum Islam terbentuk. KOS diakui sebagai yang masih murni ajarannya.
Berbulan lalu sempat tersebar foto berisi satu orang yang menggendong satu orang lainnya. Menukil artikel dari National Geographic, foto monokrom itu diambil di tahun 1889, di Damaskus. Orang yang menggendong itu bernama Muhammad, ia Muslim. Sedangkan yang digendong bernama Samir, penganut Kristen. Muhammad yang buta menjadi kaki bagi Samir yang lumpuh. Mereka bekerja di kedai kopi yang sama. Juga tinggal dalam satu atap. Mereka yatim-piatu. Beberapa pekan setelah Samir wafat, Muhammad menyusul di samping sahabatnya tersebut.
Ahmad Wahib sebagai intelektual muda muslim yang saat itu hidup di zaman yang bersamaan dengan Soe Hok Gie punya pengalaman yang mengharukan dengan penganut Kristen. Dalam catatan hariannya yang dibukukan dengan judul Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, beliau menulis, “Bagaimana aku disuruh membenci kelompok Kristen-Katolik. Aku pernah satu keluarga dengan mereka. Aku pernah tiga tahun diasuh dan dididik oleh Pastur. Aku pernah bertahun-tahun tidur, bergurau, dan bermain bersama mereka.” Pengalaman itu terjadi saat Ahmad Wahib menempuh studi di Yogyakarta. Ia tiga tahun diasuh oleh Romo H.C. Stolk S.J. dan Romo Willenborg. Kebaikan, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan para kelompok Kristen-Katolik itu yang membuatnya berharap pada Tuhannya. “Aku tak tahu, apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapaku itu ke dalam api neraka. Semoga tidak.” sambungnya.
Keindahan kebersamaan itu saya lihat juga dari keakraban keturunan Tionghoa yang tinggal di lingkungan saya. Saya sendiri memiliki teman sebaya dari mereka. Kami bermain selayaknya kanak-kanak. Tak memandang—bahkan tak peduli—agama yang di pegang. Meskipun tahu ritual ibadah yang dijalani masing-masing. Bahkan dulu masih kudengar cara mereka beribadah dengan nyanyian merdu di ujung senja yang ringan dan sederhana. Bahkan salah satu teman sebaya saya itu ada yang dikhitan dan mengadakan kenduri yang biasa dilakukan umat Muslim Indonesia. Ketika dewasa ingatan tersebut menjadi lanskap yang meneduhkan di pikiran dan perasaan. Apalagi ketika melihat ada peristiwa yang mencederai keindahan kebersamaan dan kesamaan sebagai manusia.
Di Timur Tengah sendiri kenapa akhirnya terjadi perang saudara ada yang meyakini karena provokasi dari luar. Padahal di sana tak kurang dari lima suku dan ras saja. Berbeda jauh dengan di Indonesia yang beragam. Akhirnya kembali pada ciri orang Indonesia yang memiliki selera humor tinggi. Menertawakan hal-hal yang orang-orang pertengkarkan. Karena pada dasarnya perspektif paling tinggi itu adalah humor. Kita bisa melihat sosok Gus Dur yang menyikapi sesuatunya dengan humor cerdas. Salah satu humor beliau yang kusukai yaitu saat orang lain menganggap atau menyebut kita kafir, menurut beliau, “ya sudah tinggal syahadat lagi saja”. Paling tidak dengan begitu, menjalani hidup pun akan menjadi lebih kalem. Barangkali cara sikap seperti itulah yang membuat Horace Walpole menganggap “dunia adalah komedi bagi mereka yang memikirkannya, atau tragedi bagi mereka yang merasakannya.” Menilik beberapa peristiwa teror di Indonesia, yang malah menjadi tontonan warga sekaligus kebutuhan konten media sosial, bahkan menjadi ladang yang lapang untuk pedagang asongan. Layaknya sedang menonton penggarapan film spionase.
Saya membayangkan kebosanan seperti apa yang akan terjadi jika hidup hanya diisi persamaan (dalam bentuk ideal), yang bisa jadi kebosanan itu akan beranak-pinak menjadi bentuk kebosanan yang lain. Hidup akan terasa monoton stagnan. Bukankah Tuhan menyajikan sisi yang lain agar kualitas kita sebagai manusia bertambah. Pada dasarnya, hidup ini indah, begini adanya.[]