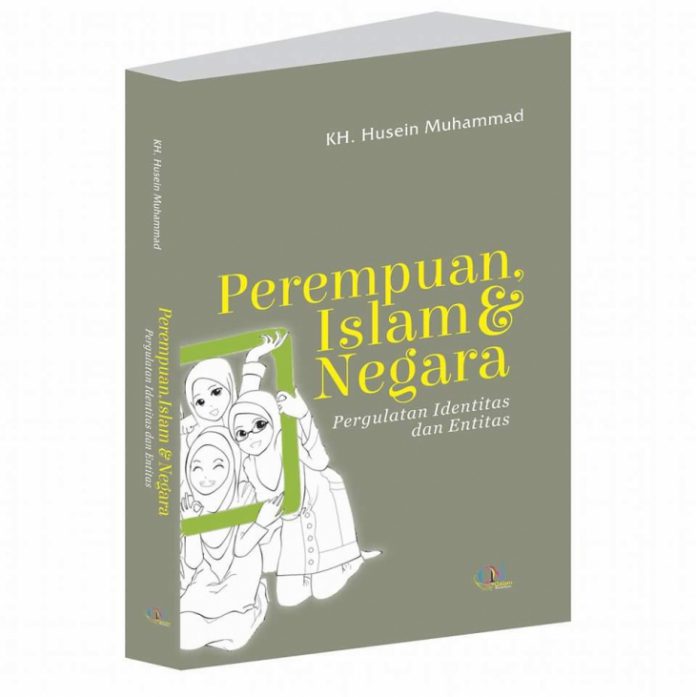Akhir-akhir ini , kita kerap menyaksikan di media dan medsos mengenai demo yang dipelopori oleh islam garis keras, atau sejuta caci- maki yang ditujukan ke sesama muslim di Facebook atau Tweeter. Mereka kadang tak segan saling membida’ahkan sampai mengkafirkan sesama, hanya karena berbeda faham dalam ajaran keagamaan. Yang diperdebatkan kadang bukan sesuatu yang substansial, tapi lebih kepada tataran praktis ‘ubudiyah atau hanya karena berpandangan yang mengedepankan sikap plural kepada agama lain, maka dikatakan sebagai kafir atau antek barat. Simbol-simbol yang mengusung agama atau mazhab tertentu bisa menjadi penyebab meruncingnya pertikaian tersebut. Ini menggambarkan fonemena ketidak dewasaan dalam beragama.
Dalam satu sisi lain, ada komunitas lain dalam hal ini pesantren dan semacamnya yang merasa nyaman dan sudah merasa harmonis dengan apa yang dikajinya, di pelajarinya, dijadikan sandaran istimbath hukumnya, tapi tanpa disadari berimbas kepada bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan. Tidak hanya itu, ada relasi timpang dalam kehidupannya, tapi justru keadaan tersebut diamini kebenarannya.
Ada pula yang menyadari ada kegelisahan, kegundahan dan ketidak adilan terhadap wacana keagamaan yang dipahaminya, tapi tidak berani mengemukakan karena khawatir su’ul adab, kehilangan “berkah” (Grace), ilmunya menjadi tidak bermanfaat tapi dengan cerdas mencari “jalan keluar” diam-diam, meski disadari betul bahwa itupun menyalahi apa yang dikaji selama ini. Misalnya suara kegelisahan santri putri / alumni yang ingin terus kuliah, berkarir, bekerja diluar negeri, menjadi kepala desa atau aktif diorganisasi dan sebagainya .Dia yakin ini menyalahi perintah sang guru ketika mengaji kitab kuning di pesantren dulu.
Penulis dalam buku ini ingin menjelaskan persoalan-persoalan tersebut, agar tidak ada lagi kegelisahan banyak melanda remaja-remaja putri pesantren, ibu-ibu majlis taklim, atau orang-orang yang ingin memperdalam islam, dalam menilai ajaran-ajaran islam yang akhir-akhir ini marak terlibat perdebatan sengit antar sesama muslim di medsos sebagaimana disebut diatas. Penulis mencoba menjawab dan mengajak pembaca untuk berpikir terbuka, menjauhi kekerasan, menghindarkan diri dari saling merendahkan sesama muslim
Penulis juga berharap pembaca mau mengkritik diri sendiri, dan menganalisa dengan kritis hal-hal tersebut dengan mengidentifikasi mana yang subtansial dan mana yang simbol agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin larut.
Perempuan dan Pesantren
Pesantren adalah institusi kegamaan yang mempunyai visi-misi mendidik, melatih dan menanamkan nilai –nilai luhur kepada santrinya tentang keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian dan kezuhudan. Tujuan pesantren adalah mencetak santri-santri yang tafaquh fiddien ( ahli dalam ilmu agama), ini terkait erat dengan hadits nabi : barang siapa ingin menjadi baik, di berikan kepadanya pengetahuan agama. .
Pesantren mempunyai tradisi keilmuan yang unik dan mandiri. Tidak ada yang mengintervensi kurikulum didalamnya, masing-masing pengasuh mempunyai kebijakan untuk menentukan kurikulum PBM. Sebagian besar pesantren di Indonesia bercorak salafi dengan mazhab syafii. Karakteristik pesantren ini sangat kuat dalam memelihara literatur-literatur keislaman klasik yang biasa dikenal dengan nama kitab kuning. Institusi ini mempunyai jargon : al Muhafadzoh ‘ala Qodim as Sholih waal Akhdz bi al jadid al ashlah . Pengajian kitab kuning ini telah berjalan berabad-abad lamanya, yang menyertai perjalanan dan kultur dalam pesantren. Keberadaan mushonif-mushonifnya begitu diagungkan, dimulyakan bahkan cenderung dimitoskan. Maka tak heran jika kemudian kitab-kitab kuning ini di anggap final dengan tanpa kritik dan analisa . Perasaan pekeuwuh, suul Adab jika mencoba mempertanyakan isi fatwa pengarangnya. Secara umum, yang dikaji adalah kitab-kitab fiqih di pesantren adalah karya ulama-ulama bermazhab syafii, lebih khusus lagi mazhab syafii yang telah diformulasikan oleh imam Nawawi sebagai muharir ( editor atau selektor) dengan pola fiqih al hadits yang dominan menekankan pemahaman tekstual dibanding pemahaman rasional.
Pesantren dalam pembelajarannya lebih mengutamakan transmisi sanad kiai. Model sorogan dan bandongan adalah gambaran bagaimana proses transmisi itu berjalan. Dengan adanya sanad yang jelas orang tidak akan banyak berkata. Proses ini dianggap sebagai keberkahan bagi santri. Disamping itu, santri dan ustadz akan menganggap hebat santri yang hafal Quran, hadit, snadzom, qoidah, syair atas yang lainnya. Dalilnya adalah al hafidz hujjah ‘ala man yahfadz artinya orang yang hafal adalah argumen bagi yang tidak hafal. Kebanyakan kitab-kitab yang dijadikan refrensi kurikulum di pesantren adalah kitab-kitab mu’tabaroh
Santri perempuan di pesantren salaf mempunyai kekhususan atau perbedaan dibanding santri putra. Perbedaan itu mencakup hak dan kewajiban, relasi pergaulan, Jadwal keluar pesantren, cara berpakaian juga materi pembelajaran yang berbeda, dimana santri putri lebih ditekankan memperdalam hafalan quran dan belajar fiqih ibadah praktis yang berkaitan dengan dirinya sebagai perempuan dan sebagai hamba Allah seperti bab sholat, mengaji al-quran, fiqih munakahaat : Qurrot al Uyoun, uqqud al Lujayn, bab hed biasanya kitab risalatul mahidz sebuah kitab hed hasil penelitian imam Syafii, dan semacamnya.
Melihat kondisi pesantren dan dunianya tersebut diatas, maka dapat difahami bahwa ada banyak ketimpangnya relasi dan bias gender di pesantren. Penulis menyatakan : “ siapapun yang membaca kitab-kitab diatas secara harfiah tanpa analisis yang luas dan kritis akan menyimpulkan dengan mudah bahwa secara umum kitab-kitab kuning tersebut memuat wacana keagamaan yang bias gender. “Sehingga diperlukan cara membaca yang berbeda, yaitu membaca atau memahaminya secara kontekstual, pembacaan yang disertai dengan analisa, sekaligus memasukan kajian sosiologis, budaya serta politik pada zaman mushonif berada. Sebuah zaman yang telah lewat berabad-abad lampau dimana budaya patriarkhi sangat melekat kuat, dan karena hampir semua kitab-kitab mu’tabaroh dikarang oleh laki-laki.
Pelestarian pembacaan literatur klasik yang apa adanya akan berdampak besar terhadap santri perempuan, termasuk juga menumbuh-suburkan diskriminasi, ketidak adilan, ketidak setaraan disetiap lini kehidupan perempuan seperti lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan bahkan negara.
Perempuan, Islam dan Negara
Sekarang kembali marak gerakan masyarakat yang menyerukan kembali Indonesia menjadi negara khilafah islamiyah (negara teokrasi), sebuah sistim politik berbasis agama. Dulu tepatnya tahun 1923, Indonesia pernah memperdebatkannya dengan alot, sampai akhirnya sepakat memilih pancasila sebagai dasar negara, karena sila-sila didalamnya mampu mengayomi keberagaman agama, ras, etnis di Indonesia. Ada banyak pertanyaan, sebenarnya islam itu semata-mata dien ataukan ia adalah agama dan negara??. KH Husein mencoba menjelaskannya, bahwa agama banyak difahami orang sebagai keyakinan dan moral individu. Sementara penulis menyatakan tidak hanya terbatas dalam makna tersebut, tapi juga mempunyai makna hukum-hukum agama ( Syariat/ al Syariaah) yang terkait dengan aturan-aturan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dapat disimpulkan agama itu mencakup keyakinan tentang Tuhan, ajaran yang mengatur ritual ibadah, dan ahlak atau moral, termasuk didalamnya etika kemanusian universal: kesetaraan, keadilan, kejujuran dan lainnya.
Di luar area tersebuat ada Mu’amalat ( relasi sosial ) disebut juga syariat atau jalan hidup. Dalam dimensi ini al Quran tidak mengatur detailnya, tapi hanya menetapkan prinsip dan etikanya belaka, maka muamalah bersifat dinamis, terbuka, juga sebagai ruang publik yang bisa diperdebatkan maupun dikritisi. Syariah karena sumber-sumber teksnya berasal dari Tuhan dia sakral, tapi sisi formula dan mekanismenya ia profan dan terbuka bagi setiap aspirasi publik. Oleh karenanya syariah bersifat kontekstual, dinamis dan inklusif. Dapat difahami jika hukum syariah selalu berbeda dalam setiap tempat, waktu dan zaman seiring dengan perkembangan sosialnya.
Sementara negara, adalah institusi publik berdasar kontrak dengan tujuan memberikan perlindungan warganya, menjadi fasilitator dan ediator dan bertanggung jawab terhadap konflik sosial, maka domain keduanya adalah berbeda namun saling melengkapi, negara mengatur domain publik, dengan membuat kebijakan publik yang menghindarkan diri dari simbol-simbol agama tertentu yang mengandung muatan diskrimainatif dengan diktum yang tidak ambigu dan tidak multi interpretasi. Oleh karenanya negara tidak berhak mengintervensi urusan keyakinan, moral, eksperesi, tata cara berpakaian, serta kebudayaan seseorang. Urusan tersebut hendaknya diserahkan oleh norma agama dan adat masing-masing daerah. Dari pemaparan ini tidak ada dikotomik antara negara dan agama, selagi keduanya menempatkan misi yang sama dalam hal penegakan keadilan, mewujudkan kesejahteraan sosial serta menjunjung tinggi basis nilai dan moral. Sebagaimana ibnu Qoyim berkata : Dimana ada keadilan, disitulah hukum Tuhan, dimana ada kebaikan disitulah hukum Tuhan
Bertanya tentang bagaimana posisi perempuan dihadapan negara dan agama? Penulis memaparkan jawabannya bahwa eksistensi perempuan dalam negara/ bangsa masih terombang-ambing dalam ambiguitas hingga detik ini. Negara melihat perempuan masih dengan dua wajah. Pada satu sisi, negara menawarkan keramahannya sebagai bentuk tanggung jawab melindungi dan melayani warganya dengan cara ikut meratifikasi DUHAM melalui UU no 39 tahun 1999, UU PKDRT , UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTTO), UU perlindungan anak, UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negri termasuk Inpres 2000, tentang pengarustamaan Gender. Ini dilakukan memenuhi mandat konstitusional negara.
Namun dalam praktek operasionalnya, banyak uu, kebijakan dan perpu dikeluarkan dengan tujuan mengayomi perempuan, tapi malah menjebak perempuan dalam perangkap diskriminisi. Sebut saja UU Pornografi, UU PNPS ( penyalahgunaan dan penodaan agama ), termasuk lahirnya perda-perda sebagai imbas desentralisasi kerap melahirkan ketidak adilan dan menyudutkan perempuan, contohnya perda qonun jinayat yang disahkan 27 september 2014, didalamnya meliputi hukum khalwat, cambuk, duduk mengangkang , serta jilbab. Negara dan agama dalam hal ini mempunyai cara pandang yang sama yaitu pandangan ambigu terhadap perempuan. Menyatakan bahwa Tuhan menjadikan agama dalam rangka menciptakan keadilan dan kasih sayang rahmatan lil a’lamin, termasuk juga sepakat bahwa didalamnya ada prinsip kesetaraan dan kehormatan martabat manusia di hadapan Tuhan, tetapi dengan merujuk teks keagamaan yang sama juga, keduanya mendiskriminasi perempuan dan menstigmatisasi perempuan sebagai sumber fitnah dan kerusakan sosial.
Persoalan ini tidak berhenti sampai disitu, merembet ke pelbagai masalah, misalnya perempuan dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak dan kewajiban, seksualitas dalam keluarga, kesehatan reproduksi, usia perkawinan, waris perempuan, perempuan dan buruh migran dan sejenisnya yang semuanya butuh solusi dengan tidak terjebak pada ambiguitas ranah agama dan negara.
Menurut penulis, lahirnya ambiguitas dalam isu-isu gender ini karena adanya perbedaan dalam membaca atau memahami teks, meskipun sumber refrensinya sama yaitu al quran. Lebih lanjut ia menyatakan bisa jadi dua faktor berikut ini menyebabkan lahirnya ambigu yaitu, (1) Sayidina Ali berkata : Al Quran adalah teks-teks suci yang tidak bisa bicara sendiri, (2) Keberadaan tafsir versus takwil, dimana tafsir lebih mendahulukan dan mencukupkan diri pada riwayat penukilan sebagai sumber berita sementara takwil lebih mementingkan pemahaman / diroyah dengan menganalisa makna substantif. Yang pertama dikatakan sebagai aliran literalis sementara yang kedua disebut sebagai progresif, karena baginya teks itu mengandung arti yang dinamis dan berproses secara terus menerus.
Di dalam Buku Perempuan, Islam dan Negara sangat menarik untuk menguliknya. Dimana menguraikan secara detail persoalan-persoalan kekinian. Termasuk bagi remaja putri pesantren dan ibu-ibu yang tengah merintis karir yang keduanyaa masih ada dipersimpangan jalan mencari identitas dan etintas. Kebisuan, kegelisahan terhadap persoalan-persoalan fiqih yang membelenggu selama ini mampu diuraikan dengan menarik oleh penulis, jangan khawatir dengan dalil-dalil naqli yang sekarang mulai marak dipertanyakan sekelompok komunitas ketika menjawab sebuah persoalan karena jargon mereka : Kembali kepada al-Quran dan Hadits. Penulis dalam hal ini kyai Husein memberikan argumentasi dari beberapa sudut pandang yang sama-sama merujuk kepada teks/ nash al-Quran, hadits, ushul Fiqih dan lainnya. Tidak hanya merubah persepsi , tapi buku ini mampu membuat seseorang menemukan substansi dari nilai-nilai yang diajarkan al-Quran tentang hak-hak dasar kemanusian, yang pada akhirnya menjadikan diri kita berhijrah kepada kearifan, menjunjung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, tasamuh dalam memandang perbedaan sampai kepada titik puncak yaitu mengimplementasikan kedalam kehidupan dalam bentuk kebijakan untuk perlindungan dan kesejahteraan sesama manusia, khususnya perempuan. Amiiin..
*Makalah disampaiakan oleh Hj Afwah Mumtazah, M.Pd.I (Rektor ISIF Cirebon) dalam acara Bedah Buku “Perempuan, Islam dan Negara; Pergulatan Indentitas dan Entitas” di Cirebonese Corner IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Rabu, 20 April 2016.